
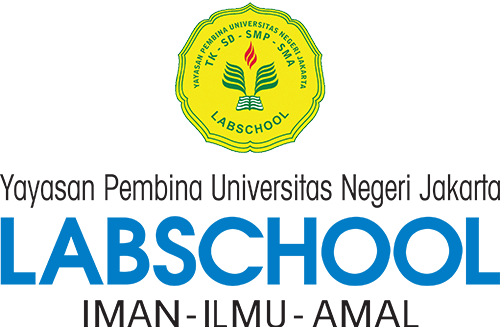
Menyongsong Era 5.0: Tantangan Peradaban dan Revolusi Pendidikan

Pendahuluan: Era Baru Kehidupan Manusia
Jepang menjadi negara pertama yang mempersiapkan diri menyambut kehidupan berbasis big data dan digitalisasi menyeluruh. Dalam ajang World Economic Forum (WEF), Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan visi Society 5.0—sebuah konsep masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sekadar efisiensi ekonomi. Konsep ini sejatinya sejalan dengan sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sebuah cita-cita yang juga menjadi arah dan tujuan pembangunan bangsa kita. Namun, pertanyaannya: apakah Indonesia telah siap menyongsong era masyarakat 5.0?
Kesiapan Indonesia dan Tantangan Nyata
Tanda-tanda transformasi digital memang mulai tampak. Pemerintah telah mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin dan panas bumi. Namun, langkah ini baru menyentuh aspek revolusi industri—belum sepenuhnya mengarah pada Society 5.0. Tantangan terbesar Indonesia masih terletak pada kesenjangan digital, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Akses teknologi dan pendidikan yang belum merata membuat digitalisasi berjalan terseok-seok. Situasi global yang VUCA—Volatile (bergejolak), Uncertain (tidak pasti), Complex (rumit), dan Ambiguous (tidak jelas)—kian memperberat langkah. Pandemi Covid-19 telah memperlihatkan betapa rentannya sistem ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan kita. Bahkan, arah kebijakan politik pun turut bergejolak. Dalam konteks pendidikan, guru menjadi ujung tombak transformasi digital, namun banyak di antara mereka yang masih terbatas dalam literasi teknologi dan belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Akibatnya, semangat perubahan sering kali tak diimbangi dengan kemampuan yang sesuai.
Analogi Peradaban dan Dunia Pendidikan
Peradaban manusia berevolusi dari zaman berburu, bertani, industri, hingga digital. Kini dunia bergerak menuju Society 5.0—sebuah fase ketika manusia dan teknologi hidup dalam harmoni. Jika ditarik analoginya, tahapan pendidikan kita mencerminkan perjalanan peradaban manusia itu sendiri: Taman Kanak-Kanak = Zaman Berburu Anak pada usia ini aktif bergerak, mengeksplorasi, dan mencari pengalaman baru. Menurut Montessori, masa ini merupakan periode emas perkembangan sensorimotor. Seperti manusia purba yang berpindah-pindah mencari makanan, anak usia dini pun bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas lain untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Sekolah Dasar = Zaman Bercocok Tanam Anak mulai belajar berproses, menanam nilai disiplin, serta berlatih tanggung jawab. Mereka melakukan proyek-proyek sederhana untuk mengasah life skill sebagai bekal hidup. Sekolah Menengah Pertama = Masa Transisi Di usia remaja, terjadi perubahan psikologis yang signifikan. Peran pendidikan menjadi penting dalam mengarahkan potensi dan mengelola emosi. Sekolah Menengah Atas = Jembatan Era Industri dan Digital Tahap ini seharusnya memperkuat nalar kritis, kreativitas, serta literasi teknologi. Namun, sistem evaluasi yang masih berorientasi pada nilai dan ujian kerap menimbulkan tekanan akademik dan masalah kesehatan mental pada siswa. Perguruan Tinggi = Era Masyarakat 5.0 Pada tahap ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, berinovasi, dan menciptakan solusi yang berkeadilan sosial. Mereka menjadi pelaku utama transformasi digital dan kemanusiaan.
Menguatkan Fondasi di Usia Dini
Meski zaman berburu telah berlalu ribuan tahun, prinsip dasarnya tetap relevan bagi pendidikan masa kini. Pondasi peradaban justru dibangun sejak usia dini—saat anak berada pada tahap eksplorasi dan pembentukan dasar kemampuan belajar. Untuk itu, pendidikan Taman Kanak-Kanak perlu dirancang dengan stimulasi yang kaya dan menyeluruh terhadap delapan sistem sensori utama: 1. Proprioseptif — kesadaran gerak dan posisi tubuh 2. Vestibular — keseimbangan dan orientasi ruang 3. Taktile — kepekaan sentuhan dan rasa kulit 4. Visual — kemampuan persepsi penglihatan 5. Auditori — pendengaran dan respon terhadap bunyi 6. Gustatori — kemampuan mengenali rasa 7. Olfaktori — kepekaan terhadap aroma 8. Interoseptif — kesadaran diri dan sensasi internal tubuh Melalui kegiatan bermain dan bergerak, anak-anak mengembangkan seluruh sistem ini secara alami. Inilah dasar dari kemampuan belajar sepanjang hayat. Jika stimulasi ini terabaikan, maka akan muncul kerapuhan dalam tahap pendidikan berikutnya—baik secara kognitif, emosional, maupun sosial.
Penutup: Menuju Masyarakat 5.0 yang Berkeadilan
Menyongsong Era 5.0 bukan hanya soal menghadirkan teknologi canggih, tetapi juga membangun manusia yang berkarakter, kreatif, dan berkeadilan sosial. Pendidikan anak usia dini harus menjadi titik awal transformasi peradaban—tempat di mana anak belajar menjadi manusia seutuhnya. Melalui penguatan fondasi sensori, nilai, dan keterampilan hidup, generasi masa depan akan tumbuh menjadi manusia yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga tangguh menghadapi ketidakpastian zaman.
“Pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.” (Ki Hajar Dewantara)
Daftar Pustaka
Abe, S. (2019). Society 5.0: Human-Centered Society. World Economic Forum, Davos.
Dewantara, K. H. (1967). Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian I: Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
Montessori, M. (1967). The Absorbent Mind. New York: Dell Publishing.
Tagore, R. (1929). Creative Unity. London: Macmillan.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Profil Pelajar Pancasila dan Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Kemendikbudristek.
World Economic Forum. (2020). The Global Competitiveness Report 4.0: Preparing for the Future of Work. Geneva: WEF Publications.

Awalludin, S.Pd.
Guru KB-TK Labschool UNJ
Leave a Replay
Komplek UNJ, Jalan Pemuda, RT. 7 / RW. 14, Rawamangun, RT.7/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
Get In Touch
info@labschool-unj.sch.id
(021) 4786 0038 (Hunting)
Quick Links
© LABSCHOOL UNJ




