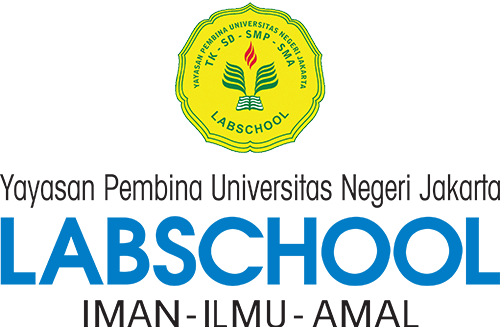

KB-TK Labschool merupakan satuan pendidikan yang mengadopsi sistem sekolah inklusi, pada implementasinya KB-TK Labschool menerima pelbagai latar belakang dan karakteristik anak dalam proses pembelajarannya termasuk anak berkebutuhan khusus. Salah satu layanan program utama yang diberikan untuk menstimulasi perkembangan anak berkebutuhan khusus di KB-TK Labschool adalah program practical life dan program healthy morning. Pada teknis kedua program tersebut, anak berkebutuhan khusus akan dipisahkan dari lingkungan kelas-nya untuk mendapat program dari guru pendidikan khusus upaya menstimulasi perkembangan kemampuan kehidupan sehari-hari (activity daily living), perkembangan motorik kasar & halus, serta kemampuan literasi dan numerasi awal. Yang menjadi pertanyaan dalam penulisan ini, adalah “apakah memisahkan anak berkebutuhan khusus dalam beberapa momen dari lingkungan kelasnya merupakan tindakan yang tepat?.” Meski pada tataran yuridis di Indonesia tidak sama sekali menyalahi aturan tersebut, tetapi dalam tulisan ini akan menyoroti isu tersebut menggunakan sudut pandang prinsip prima facie duty W.D. Ross.
Sejarah & Definisi Pendidikan Inklusif
Negara-negara Scandinavia adalah negara yang memprakarsai konsep pendidikan inklusif, hingga akhirnya Amerika dan Inggris mengadopsi konsep tersebut pada negaranya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif semakin nyata sejak diadakannya konvensi dunia mengenai hak anak pada tahun 1989, dan tentang dunia pendidikan di tahun 1991 yang diselenggarakan di Bangkok hingga menelurkan sebuah deklarasi “Education for All”. Tahun 1994 dalam upaya melanjutkan deklarasi tersebut, diselenggarakan-lah konvensi di Spanyol serta mencetuskan pendidikan inklusif yang termaktub dalam “the Salamanca Statement on Inclusive Education.” Di Indonesia meski sudah lebih awal dengan diluncurkannya program pendidikan terpadu di tahun 1980-an, karena kurang berkembang akhirnya baru muncul kembali di awal tahun 2000-an. Pendidikan inklusif di Indonesia mulai berkembang kembali di tahun 2004 dengan diadakannya Deklarasi Bandung, dan ditindaklanjuti dalam semangat penyelenggaraan simposium internasional Bukittinggi tahun 2005 dengan membuahkan “Rekomendasi Bukittinggi”.
Dalam landasan yuridis di Indonesia, definisi mengenai pendidikan inklusif secara spesifik dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang menyatakan sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi peluang kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau proses pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Beberapa organisasi besar seperti UNESCO mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai suatu pendekatan pendidikan dengan memandang setiap peserta didik sebagai individu unik sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Definisi pendidikan inklusif menurut Sapon & Shevin (2007) diartikan sebagai sistem layanan pendidikan khusus yang mewajibkan setiap anak dengan kebutuhan khusus dan anak dengan perbedaan untuk mendapat layanan pendidikan di sekolah-sekolah terdekat, di dalam kelas reguler bersama dengan teman sebayanya. Sedangkan Masruroh & Hendriani mendefinisikannya sebagai pengajaran inklusif yang merupakan suatu metode pendidikan dengan mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus untuk bersama pada sekolah umum, hingga pada akhirnya mereka menjadi salah satu bagian dari lingkungan tersebut.
Dari beberapa definisi mengenai pendidikan inklusi yang telah dijabarkan di atas, terdapat kesamaan konsep dan konteks ruang & waktu, yaitu ter-integrasinya anak berkebutuhan khusus untuk mendapat layanan program pendidikan bersama-sama dengan anak reguler di lingkungan pendidikan pada umumnya.
Konsep Prima Facie Duty W.D.Ross

Istilah Prima Facie Duty pertama kali dipopulerkan oleh Sir William David Ross (1877-1971) seorang filsuf asal Skotlandia. Istilah Prima Facie berasal dari bahasa Latin, prima yang berarti “pertama” dan facies yang berarti “wajah”. Dalam karier akademisnya, Ross berhasil mempublikasikan 2 buku penting dalam filsafat moral yaitu The Right and the Good (1930) dan Foundation of Ethics (1939). Pembahasan mengenai Prima Facie sebenarnya dibahas dalam bagian ke dua pada buku The Right and the Good yang diberi judul What Makes Right Acts Right. Dalam tulisannya, Ross mencoba untuk membuat skenario keputusan terbaik bila kita disituasikan dimana terdapat dua kewajiban moral yang mengikat. Berbeda dengan Utilitarian Moore yang berprinsip “mana tindakan yang menghasilkan lebih banyak kebaikan”, Ross lebih memilih untuk menggunakan kalimat “mendesak” dalam memutuskan sebuah tindakan. Ross dalam tulisannya tidak memberi kita finalisasi jawaban dalam situasi tersebut, tetapi menekankan kita untuk mempelajari sebuah situasi sedalam mungkin bila kita berada di kondisi tersebut – dua kewajiban moral yang mengikat.
Ross mengusulkan terdapat 7 (tujuh) klasifikasi kewajiban moral yang mengikat kita, dengan tidak menyatakan bahwa daftar ini telah final atau lengkap, antara lain: kewajiban kesetiaan (fidelity), kewajiban reparasi (reparation), kewajiban rasa terima kasih (gratitude), kewajiban keadlian (justice), kewajiban kebaikan (beneficence), kewajiban pengembangan diri (self improvement), dan kewajiban untuk tidak merugikan (non-maleficence). Usulan ini didasari atas hal yang sama pada teori saingannya, daftar kebaikan (goods) – yaitu refleksi langsung atas yang sebenarnya kita yakini.
Ross dalam tulisannya memberikan contoh kasus, apabila kita disituasikan untuk memenuhi sebuah janji yang telah dibuat – entah mungkin secara tersirat (duty of fidelity), di situasi yang tidak terduga kita dihadapkan dengan kondisi untuk membantu orang agar selamat atas kecelakaan. Ross mempercayai dengan memberi alasan bahwa kita dapat melonggarkan janji yang telah kita buat, untuk membantu korban agar selamat dari peristiwa kecelakaan. Meski dilihat keduanya sama-sama memiliki manfaat kebaikan yang sama besar, tetapi karena kondisi yang mendesak kita dapat membantu orang agar nyawanya selamat atas kecelakaan meski kita tidak memiliki janji apapun padanya.
Mengenai Program-program Inklusi KB-TK Labschool
Aktualisasi KB-TK Labschool dalam upaya turut serta menciptakan ruang inklusi dalam lingkungan pendidikan, membuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di satuan pendidikan-nya. Terdapat 5 program yang diarus-utamakan dalam menstimulasi perkembangan anak berkebutuhan khusus, antara lain ; Program Practical Life (PPL), Program Sensory Movement (PSM), Program Sensory Swimming (PSS), Program Healthy Morning (PHM), dan Program Literasi & Numerasi (PLN). Dalam teknisnya 3 program seperti PSM, PSS, dan PLN diberikan setelah atau di luar jam pembelajaran atau dikenal ekstrakurikuler, dan 2 program; program practical life dan program healthy morning dilaksanakan pada saat jam pembelajaran berlangsung – atau intrakurikuler. Program healthy morning dan practical life melibatkan pemisahan anak berkebutuhan khusus dari lingkungan kelasnya, untuk ditarik keluar dari kelasnya ke ruang yang telah tersedia dan mendapat stimulasi dari guru pendidikan khusus. Di sini-lah letak narasi yang menjadi refleksi mendalam, apakah pemisahan anak berkebutuhan khusus dalam beberapa momen tertentu dari lingkungan kelasnya merupakan tindakan yang tepat?
Refleksi atas situasi Prima Facie Duty dalam Program Inklusi KB-TK Labschool
KB-TK Labschool dalam semangat Education for All, pada implementasinya secara teknis terdapat lima program untuk menstimulasi anak berkebutuhan khusus. Saya tidak akan membahas tiga program antara lain program sensory movement, program sensory swimming, dan program literasi & numerasi, karena pada implementasinya tiga program tersebut tidak bertabrakan sama sekali dengan muatan intrakurikuler yang menjadi kewajiban utama KB-TK Labschool – tidak terdapat dua kewajiban moral yang mengikat. Dua program lain seperti program healthy morning dan program practical life, merupakan program yang berkenaan dengan situasi moral yang telah di jelaskan dalam contoh kasus prima facie duty di atas (dua kewajiban moral yang mengikat). Pada implementasinya pemberian stimulasi dalam program healthy morning dan practical life terdapat dalam rentang waktu intrakurikuler.
Maksud program healthy morning dan practical life dirancang sama dengan tiga program lainnya, atas dasar upaya memberi porsi lebih dan konsisten dalam menstimulasi perkembangan anak berkebutuhan khusus oleh Guru Pendidikan Khusus mengikuti karakteristik belajar anak. Meski telah terdapat kesepakatan untuk memprioritaskan kedua program tersebut dalam rentang waktu intrakurikuler karena alasan memenuhi kebutuhan perkembangan anak secara mendesak, tetapi dalam situasi lain bilamana terdapat agenda latihan rutin yang dilaksanakan pra-pagelaran, event Art Festival, Pelepasan, atau sebelum kegiatan lintas budaya. Dimana anak berkebutuhan khusus juga memiliki kewajiban yang sama-sama mendesak untuk melakukan latihan dalam menyiapkan mereka tampil bersama dengan rekan sebayanya menjelang pelaksanaan kegiatan, mana yang lebih menjadi kewajiban utama anak, mengikuti latihan pra-kegiatan? Atau tetap berjalan pada koridor program inklusi yang telah dirancang?.
Dalam situasi ini, wajib untuk mencermati kondisi perkembangan anak dan memperhitungkan kembali durasi waktu persiapan event. Prinsip monisme (mono) bukan langkah bijak dengan men-totalitaskan anak hanya untuk mengikuti satu kewajiban – entah program inklusi yang telah dirancang maupun latihan rutin yang digelar menjelang kegiatan. Ross dalam tulisannya sangat menganjurkan kita untuk melakukan refleksi mendalam melihat situasi semacam ini. Diperlukannya strategi khusus dan komunikasi persuasif antar pihak yang bersangkutan – guru kelas dengan guru pendidikan khusus, serta pemangku kebijakan sekolah. Melihat perkembangan anak berkebutuhan khusus masih menjadi objektivitas tertinggi, tetapi tidak memukul rata atau mengeneralisir setiap anak berkebutuhan khusus di KB-TK Labschool harus didahulukan dalam menstimulasi perkembangannya oleh program inklusi. Kembali untuk memandang secara diferensiasi masing-masing anak mana yang lebih mendesak berdasar kebutuhannya, antara didahulukan stimulasi perkembangannya melalui program inklusi, atau dilonggarkan untuk dapat mengikuti prosesi latihan persiapan event. Apabila kita tetap dapat menyelaraskan kedua kewajiban dengan strategi khusus dan pertimbangan yang cermat, why not?.
DAFTAR PUSTAKA
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. n.d.
Herawati, Nenden Ineu. Pendidikan Inklusif. n.d.
Masruroh, Himamy Zahrotul, and Wiwin Hendriani. Dive into Inclusive Education for Children with Special Needs in Indonesia. n.d. https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5643.
Ross, W. D.., and Philip. Stratton-Lake. The Right and the Good. Clarendon Press, 2007.
Wardoyo, William. Kebaikan Dan Ketepatan Menurut W.D.Ross Sebagai Etika Prima Facie Duties. 2016.
Leave a Reply
Komplek UNJ, Jalan Pemuda, RT. 7 / RW. 14, Rawamangun, RT.7/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
Get In Touch
info@labschool-unj.sch.id
(021) 4786 0038 (Hunting)
Quick Links
© LABSCHOOL UNJ